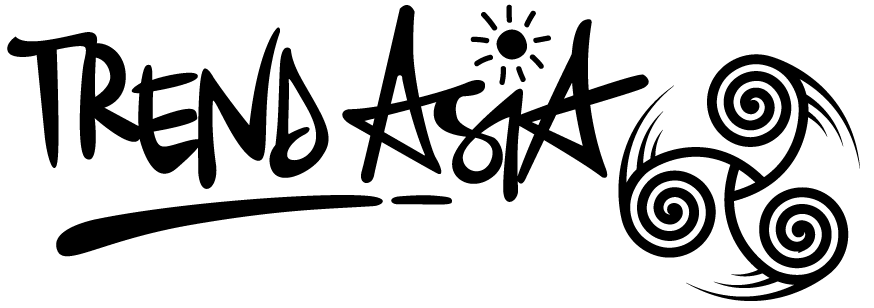Jakarta, 22 September 2022–Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres EBT), yang ditujukan untuk mengatur proses transisi energi Indonesia menuju energi terbarukan.
Namun, peraturan ini menyimpang dari misi aslinya: untuk mendorong energi bersih dan terbarukan sambil mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Perpres ini malah mengulur transisi dan memberi nafas pada batubara, yang selain kotor dan destruktif terhadap lingkungan, juga dibangun dalam skema yang sangat merugikan rakyat dan negara.
Aturan ini memperpanjang tenggat waktu pembangunan PLTU baru yang tersisa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dari 2023 menjadi 2032. Dalam RUPTL 2021-2030 bahkan masih ada 13,8 GW rencana pembangunan PLTU baru. [1]
Padahal, misalnya di jaringan listrik Jawa-Bali dan Sumatera – yang menjadi lokasi pembangunan intensif – sudah kelebihan daya (oversupply). Ditambah dengan muatan yang akan dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit baru, angka oversupply di jaringan ini bisa lebih dari 60% pada tahun 2030.
Gencarnya pembangunan ini disokong oleh skema take or pay, yang mengharuskan PLN untuk tetap membayar kapasitas yang ada–termasuk dari pembangkit swasta yang kini mendominasi–meskipun listrik tersebut tidak diperlukan. Pembangunan pembangkit menjadi bisnis aman yang diminati investor, tetapi sangat merugikan negara yang harus menebus kerugian PLN.
Sangat tidak patut bahwa untuk menyikapi kerugian hasil kesalahan tata kelola berkepanjangan berlatar belakang konflik kepentingan ini, pemerintah berkeinginan untuk tetap menambah pasokan listrik dalam jaringan. [2] Gencarnya pembangunan pembangkit juga ini bertolak belakang dengan rencana pemensiunan dini pembangkit batubara. Pembangkit-pembangkit ini berisiko menjadi aset terlantar dan akan menambah pengeluaran tidak perlu bagi negara untuk memensiunkannya.
Pembangunan PLTU: Izin Lingkungan Sering Bermasalah dan Ditolak Warga Sekitar
Pemerintah seharusnya dapat mengendalikan pembangunan pembangkit melalui pemberian izin. Namun, mereka malah longgar dan sembarangan dalam membagikan izin ini. Misalnya pada rencana pembangunan PLTU Tanjung Jati A, yang sedang digugat karena izin AMDAL-nya tidak menyertakan kajian dampak emisi karbon dan perubahan iklim. [3]
Selain pemberian izin yang serampangan, pemerintah juga masih memberi celah bagi PLTU batubara berusia tua agar tetap beroperasi, yang justru akan menggagalkan usaha untuk transisi ke energi bersih dan berkeadilan.
Pemerintah tampak acuh kepada masalah-masalah batubara ini, situasi tersebut menunjukkan betapa lemahnya ambisi mereka dalam meningkatkan bauran energi terbarukan yang juga masih didominasi batubara.
“Perpres ini tetap ingin melanggengkan penggunaan batubara dengan mekanisme lain sehingga dapat memperpanjang usia PLTU yang seharusnya segera dipensiunkan, yaitu melalui co-firing biomassa salah satunya berbahan pelet dan serpihan kayu. Co-firing biomassa juga dapat dilihat sebagai usaha pencitraan “hijau” yang dilakukan pemerintah terhadap PLTU batubara tersebut,” kata Meike Inda Erlina, Juru Kampanye Biomassa dan RE Trend Asia.
Padahal co-firing batubara tidak efektif mengurangi emisi, dan bahkan berpotensi menambah emisi dari pembakaran di PLTU dan deforestasi dari pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE). Pemerintah mau menekan emisi dari sektor energi, tetapi malah akan menambah emisi dari sektor FoLU (Forestry and Other Land Uses). [4]
Gimik Transisi Energi Menjelang G20 dan COP
Lemahnya komitmen pemerintah dalam transisi energi bersih ini berbanding terbalik dengan komitmen verbal Jokowi tahun lalu. Perpres ini tampak seperti sekadar gimik politik menjelang G20 dan COP27 (Conference of Parties).
“Keberadaan Perpres ini hanya gestur politik dan bualan Jokowi menjelang G20 dan COP27. Apabila mengamati secara mendasar, Perpres ini seperti perubahan kosmetik agar Indonesia tampak progresif di hadapan publik internasional. Nyatanya pemerintah tetap memfasilitasi kepentingan oligarki batubara,” ujar Andri Prasetiyo, Peneliti dan Juru Kampanye Energi Trend Asia.
Publik Indonesia serta negara-negara G7 dan G20 harus tetap menyoroti Perpres ini dengan kritis. Kita juga perlu menyoroti aktor-aktor batubara yang berkelindan erat dengan pemerintahan dan sarat dengan potensi konflik kepentingan. Jika komitmen pemerintah untuk transisi energi terbarukan bukan sekadar omong kosong, mereka harus menunjukkan sikap lebih tegas terhadap industri batubara.
Catatan Editorial:
[1] https://trendasia.org/gerakan-bersihkanindonesia-gugat-klaim-hijau-ruptl-2021-2030/ [2] https://antikorupsi.org/id/article/siapa-di-balik-proyek-pembangkit-listrik
[3] https://s.id/BriefingPaper_PLTUTanjungJatiA
[4] https://trendasia.org/riset-membajak-transisi-energi-seri-1-adu-klaim-menurunkan-emisi/
Photo by Thomas Reaubourg on Unsplash