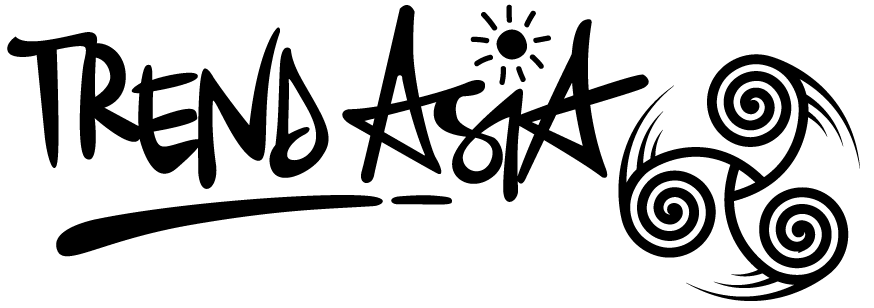Jawa Pos-Dalam rekam jejaknya, industri perkayuan Indonesia juga erat dengan perampasan lahan dan praktik buruk yang mendorong konflik warga. Padahal dalam penelitian Trend Asia, untuk proyek co-firing biomassa 10 persen di seluruh PLTU yang dicanangkan pemerintah, dibutuhkan lahan sebanyak 2,33 juta hektare, atau 35 kali luas DKI Jakarta. Potensi praktik buruk dalam pengadaan ini akan sangat besar.
Masalahnya, industri biomassa dalam bentuk pelet kayu di Indonesia selama ini bukan hanya dilakukan untuk kebutuhan domestik. Ia juga diekspor untuk kebutuhan listrik Jepang dan Korea. Data Trend Asia, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia sudah mengekspor hampir 800 ribu ton pelet kayu, termasuk sebanyak 43,8 ribu ton ke Jepang, yang merupakan salah satu negara investor dalam skema JETP.
Masuknya co-firing biomassa ke dalam skema pendanaan JETP akan semakin mendorong pengembangan biomassa kayu yang bermasalah. Negara yang mengembangkan bioenergi dari kayu sebagai sumber energi terbarukan, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Denmark, dan Jepang, akan semakin didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan biomassa kayu guna menjamin suplai untuk negara mereka sendiri. Denmark misalnya, telah menjajaki kemungkinan investasi pembangkit dan penyediaan biomassa di Sumbawa.
Baca Juga: Co-firing biomassa dianggap tak pantas masuk pendanaan JETP
Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Oktaviani menyebutkan bahwa ketergantungan kepada negara-negara investor terkait bentuk pengembangan energi terbarukan, menunjukkan Indonesia tidak berdaulat dalam menentukan sumber energi terbarukannya. “Dengan memasukkan bioenergi dan melegitimasi kayu sebagai bahan bakar energi terbarukan dalam dokumen CIPP JETP, menjadi jalan klaim bagi negara investor pengembang industri biomassa, bahwa mereka telah mewujudkan energi terbarukan. Tapi dengan mengorbankan hutan alam di Indonesia,” ujarnya.
Foto: Melvinas Priananda/Trend Asia